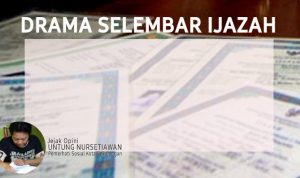Oleh: Rokhmat Widodo, pengamat politik
September bagi bangsa Indonesia tidak hanya identik dengan aroma pergantian musim, jatuhnya hujan pertama setelah kemarau panjang, atau suasana lengang di antara liburan panjang kalender akademik. September dalam catatan sejarah negeri ini justru menyimpan luka yang berulang kali menggores hati rakyatnya.
Dalam ingatan kolektif bangsa, September sering dipandang sebagai bulan kelabu, bulan yang menghadirkan duka, tragedi, dan peristiwa-peristiwa berdarah yang meninggalkan jejak panjang dalam perjalanan republik. Dari tragedi politik, konflik sosial, hingga kekacauan ekonomi, September seakan menjadi pengingat bahwa bangsa ini masih terus berjuang untuk menemukan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
Salah satu peristiwa paling kelam yang tidak bisa dilepaskan dari bulan ini adalah tragedi 30 September 1965, yang kemudian dikenal dengan G30S. Peristiwa yang meletus pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober ini mengubah peta politik Indonesia secara drastis. Enam jenderal Angkatan Darat dibunuh, suasana nasional menjadi penuh ketegangan, dan rakyat dicekam rasa takut. Sejarah kemudian mencatat bagaimana tragedi ini menjadi pintu masuk lahirnya rezim baru yang bertahan selama lebih dari tiga dekade. Namun, di balik narasi resmi negara, masih terdapat begitu banyak misteri, kontroversi, dan versi-versi lain yang hingga kini belum pernah sepenuhnya terungkap.
Pertanyaan siapa dalang sesungguhnya, bagaimana proses pembunuhan massal yang terjadi setelahnya, serta berapa jumlah korban yang sebenarnya, masih menjadi perdebatan panjang. Bagi banyak keluarga korban, September 1965 bukan sekadar catatan buku sejarah, melainkan luka yang diwariskan lintas generasi.
Tidak berhenti di sana, dua dekade setelahnya, September kembali menjadi bulan penuh darah dengan tragedi Tanjung Priok tahun 1984. Saat itu, rakyat yang berusaha menyuarakan aspirasi keagamaan dan politiknya harus berhadapan dengan moncong senjata aparat. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi pembantaian. Puluhan, bahkan ratusan orang meregang nyawa. Darah bercucuran di jalanan, dan hingga kini, banyak keluarga korban yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Tragedi ini menambah panjang daftar kelam September bangsa Indonesia, sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi kala itu di bawah bayang-bayang kekuasaan yang otoriter.
Memasuki akhir dekade 1990-an, bangsa ini kembali menyaksikan betapa September menghadirkan kepiluan lain. Krisis ekonomi Asia yang melanda tahun 1997–1998 turut memberikan dampak paling signifikan pada rakyat kecil. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, nilai tukar rupiah anjlok, dan angka pengangguran meningkat tajam. September 1997 dikenang sebagai awal dari gelombang besar krisis yang membuat jutaan rakyat Indonesia jatuh ke jurang kemiskinan. Kerusuhan sosial, demonstrasi mahasiswa, hingga tumbangnya Orde Baru tahun berikutnya tidak bisa dilepaskan dari akar krisis ini. Meski tidak setragis pembantaian berdarah, September kali ini mencatat luka ekonomi yang amat dalam.
Luka yang hingga kini masih terasa dampaknya dalam ketimpangan sosial, utang negara, dan kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah.
Dalam dimensi sosial, September juga kerap menampilkan wajah muram bangsa ini. Bencana alam sering kali terjadi pada bulan ini. Gempa bumi, banjir, hingga tanah longsor beberapa kali melanda daerah-daerah di Indonesia pada bulan September, seakan mempertegas bahwa penderitaan bangsa tidak hanya datang dari konflik politik dan sosial, melainkan juga dari murka alam yang sering kali menghantam rakyat kecil. Salah satu yang paling membekas adalah gempa besar di Sumatera Barat pada September 2009 yang merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan infrastruktur vital. Walau peristiwa ini terjadi di era yang lebih baru, masyarakat tetap mengaitkan bulan September dengan duka dan kepedihan.
Jika kita melihat lebih luas, catatan September kelabu bukan hanya tentang darah, air mata, dan reruntuhan sejarah. Ia juga tentang ingatan kolektif bangsa yang terus dipaksa menghadapi kenyataan bahwa keadilan sering kali tertunda. Banyak peristiwa kelam September yang hingga kini tidak pernah mendapatkan penyelesaian hukum yang tuntas. Para korban dan keluarganya masih menanti pengakuan, rehabilitasi, atau sekadar permintaan maaf.
Namun, negara kerap menutup mata, sibuk dengan pergantian kekuasaan, dan lebih memilih melupakan daripada mengingat. Dalam kondisi demikian, September menjadi semacam pengingat tahunan bahwa luka bangsa ini belum sepenuhnya sembuh.
Namun, di balik kelamnya catatan sejarah, September juga menyimpan sisi reflektif yang seharusnya menjadi bahan renungan bersama. Bulan ini seakan memberi pesan bahwa kemerdekaan tidak hanya tentang mengusir penjajah asing, tetapi juga tentang bagaimana bangsa ini mampu mengelola perbedaan, menghadirkan keadilan, serta mencegah kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang. Setiap tragedi yang terjadi di bulan ini adalah alarm yang seharusnya membangunkan kesadaran kita, agar jangan sampai generasi mendatang mengulang kesalahan yang sama.
Sayangnya, kesadaran ini sering kali hanya menjadi retorika musiman. Setelah peringatan selesai, setelah media berhenti memberitakan, ingatan bangsa perlahan pudar, hingga tragedi berikutnya kembali hadir.
Jika kita bertanya mengapa September begitu identik dengan duka, tentu jawabannya tidak bisa dilihat secara sederhana. Ada faktor politik, ekonomi, sosial, bahkan alam yang berkelindan. Namun, lebih dari itu, September kelabu adalah simbol dari kelemahan bangsa dalam membangun sistem yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Selama sejarah bangsa masih diwarnai impunitas, selama hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, selama suara rakyat sering dibungkam dengan kekerasan, maka bulan-bulan kelabu seperti September akan terus berulang, entah dalam bentuk apa pun.
Saat ini, di tengah kondisi bangsa yang diwarnai berbagai masalah—mulai dari korupsi yang merajalela, harga pangan yang melonjak, kebijakan publik yang kerap tidak berpihak pada rakyat kecil, hingga degradasi etika pejabat—catatan September kelabu seharusnya menjadi kaca untuk bercermin.
Kita harus berani bertanya: apakah bangsa ini benar-benar belajar dari sejarah, atau justru terus mengulang pola lama dengan wajah baru? Bukankah tragedi sosial yang terjadi belakangan ini, seperti konflik agraria, bentrokan warga dengan aparat, atau diskriminasi yang masih dialami kelompok tertentu, sejatinya hanyalah bentuk lain dari tragedi-tragedi lama? Jika ya, maka September kelabu sesungguhnya tidak hanya milik masa lalu, melainkan juga milik masa kini.
Generasi muda, khususnya, memiliki peran penting untuk menulis ulang narasi September. Bukan untuk melupakan, melainkan untuk mengingat dengan cara yang lebih adil dan manusiawi. Sejarah tidak boleh hanya dilihat dari sudut pandang pemenang. Korban, mereka yang suaranya terbungkam, mereka yang keluarganya hancur, harus diberikan ruang dalam catatan sejarah bangsa. Dengan begitu, September kelabu bukan lagi sekadar duka, melainkan juga pintu menuju kesadaran baru, bahwa bangsa ini harus berdamai dengan masa lalunya agar bisa menatap masa depan dengan lebih bijaksana.
Pada akhirnya, catatan September kelabu adalah pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah yang sekali jadi, melainkan perjuangan yang harus terus diperjuangkan. Bangsa ini harus berani menghadapi luka sejarahnya, harus berani menuntaskan persoalan hukum yang tertunda, dan harus berani mengakui kesalahan yang pernah terjadi. Tanpa itu semua, September akan terus hadir sebagai bulan kelabu, bulan yang tidak pernah benar-benar mampu kita lalui dengan damai.
Maka, setiap kali September tiba, marilah kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Ingatlah bahwa di bulan ini, sejarah pernah menuliskan duka mendalam. Jangan sampai tragedi itu hanya menjadi arsip sunyi di rak-rak perpustakaan, atau sekadar bahan propaganda politik sesaat. Jadikanlah September sebagai bulan refleksi, bulan untuk memperkuat tekad membangun bangsa yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada rakyat. Karena hanya dengan cara itu, September kelabu bisa perlahan berubah menjadi September yang penuh cahaya harapan.
Namun, yang sering luput dari perhatian kita adalah bagaimana setiap peristiwa kelabu di bulan September meninggalkan warisan psikologis yang mendalam. Luka sejarah tidak hanya dirasakan oleh mereka yang menjadi korban langsung, melainkan juga keluarga, keturunan, bahkan masyarakat luas. Rasa takut, rasa tidak percaya pada negara, dan trauma kolektif menjadi bayang-bayang yang sulit dihapus.
Dalam kasus G30S misalnya, banyak anak-anak korban yang tumbuh dengan stigma sosial. Mereka dijauhkan dari pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan kerap diperlakukan tidak adil hanya karena garis keturunan. Padahal, mereka sama sekali tidak bersalah. September bagi mereka bukan hanya catatan sejarah, tetapi realitas diskriminasi yang harus dihadapi sepanjang hidup.
Tragedi serupa juga bisa kita lihat pada korban Tanjung Priok. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa pernah mengetahui di mana jasad mereka dimakamkan. Para ibu hidup dalam ketidakpastian, menunggu kepulangan anak-anaknya yang tidak pernah kembali. Negara baru memberikan pengakuan puluhan tahun kemudian, itupun tanpa pemulihan yang sepadan dengan luka yang dialami. Inilah wajah lain dari September kelabu: bulan di mana suara rakyat kecil seakan lenyap dalam kebisingan politik.
Lebih jauh lagi, September sering kali menjadi simbol bagaimana bangsa ini gagal belajar dari masa lalu. Konflik yang berulang, entah dengan wajah ideologi, agama, ekonomi, atau politik, menunjukkan bahwa akar masalah tidak pernah benar-benar dibereskan. Selama kesenjangan sosial tetap lebar, selama ketidakadilan ekonomi dibiarkan, selama hukum lebih berpihak pada penguasa daripada rakyat, maka tragedi-tragedi semacam September akan terus muncul dalam bentuk baru.
Kita hanya mengulang pola: rakyat marah, aparat bertindak represif, korban berjatuhan, lalu waktu berjalan tanpa ada penyelesaian.
Jika kita jujur, sebenarnya September bukanlah bulan yang terkutuk. Ia hanya menjadi saksi. Yang menjadikan bulan ini kelabu adalah ulah manusia itu sendiri: keserakahan politik, kebijakan yang tidak adil, serta keberpihakan penguasa pada kepentingan tertentu. September hanya kebetulan menjadi titik di mana letupan-letupan itu muncul. Tetapi karena terus berulang, ia kemudian dipandang sebagai bulan yang membawa sial bagi bangsa. Padahal, akar masalahnya bukan pada kalender, melainkan pada struktur sosial-politik yang rapuh.
Hari ini, di abad ke-21, tantangan bangsa Indonesia memang berbeda. Tidak lagi berbentuk kudeta bersenjata atau pembantaian massal, tetapi dalam bentuk yang lebih halus: korupsi yang menggerogoti keuangan negara, privatisasi sumber daya yang merugikan rakyat kecil, serta politik yang semakin jauh dari nilai Pancasila.
Namun, jika kita tidak berhati-hati, semua itu bisa saja melahirkan tragedi sosial baru yang sama kelamnya dengan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Rakyat bisa saja kembali turun ke jalan karena tidak tahan dengan beban hidup, sementara aparat bisa saja kembali menanggapi dengan kekerasan. Dan ketika itu terjadi, catatan September kelabu akan bertambah panjang.
Maka, penting bagi kita sebagai bangsa untuk menjadikan September sebagai momentum refleksi. Setiap tahun, ketika bulan ini datang, seharusnya kita mengingat kembali bagaimana sejarah menuliskan luka, bukan untuk meratapinya semata, tetapi untuk belajar agar kesalahan yang sama tidak terulang. Ingatan kolektif bangsa harus dijaga, bukan dipelintir demi kepentingan politik. Generasi muda harus dikenalkan pada fakta sejarah secara jujur, tidak ditutup-tutupi atau disajikan sepihak. Dengan cara itu, mereka bisa tumbuh sebagai generasi yang kritis, yang berani mengatakan tidak pada ketidakadilan, dan yang mampu membangun masa depan lebih baik.
Pada titik ini, September sebenarnya bisa kita ubah maknanya. Dari bulan kelabu menjadi bulan kesadaran. Dari bulan luka menjadi bulan pembelajaran. Namun, perubahan itu tidak akan datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan kesungguhan seluruh elemen bangsa: pemerintah yang mau jujur pada sejarah, aparat hukum yang benar-benar adil, akademisi yang berani bersuara, media yang tidak berpihak, serta masyarakat yang tidak mudah lupa. Jika semua itu bisa terwujud, maka mungkin suatu hari nanti, September tidak lagi dipandang sebagai bulan penuh duka, melainkan bulan di mana bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang sejati.
Karena itu, catatan September kelabu bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi juga peringatan bagi hari ini dan hari esok. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah bangsa kita apa adanya. Jika yang terlihat masih luka, masih tangisan, masih ketidakadilan, maka itu berarti pekerjaan rumah kita sebagai bangsa belum selesai. Tetapi jika suatu saat nanti September bisa dikenang sebagai bulan damai, bulan persatuan, bulan di mana rakyat merasa benar-benar merdeka, maka saat itulah kita bisa mengatakan bahwa bangsa ini akhirnya belajar dari sejarahnya. Hingga hari itu tiba, marilah kita terus mengingat, terus berjuang, dan terus berharap, agar kelamnya September tidak lagi menjadi kutukan abadi bagi negeri ini.