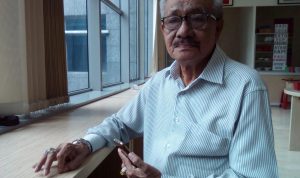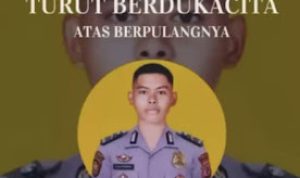Forum Literasi Filantropi Akademizi bersama Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) menggelar diskusi bertemakan “Di Balik Cerita UU Zakat Pertama di Indonesia”, Selasa (30/9). Acara ini menjadi ajang penting untuk menelusuri perjalanan panjang regulasi zakat di tanah air sekaligus menegaskan peran zakat sebagai kekuatan sosial-ekonomi bangsa.
Wakil Dekan FIB UI Untung Yuwono menyampaikan kebanggaannya atas terselenggaranya acara ini. “Kami merasa bangga FIB mampu memperkuat literasi filantropi Indonesia. UU Zakat hanyalah pintu masuk sejarah. Diskusi zakat terus berkembang, karena zakat adalah kewajiban yang berdampak luas,” ujarnya.
Untung menekankan bahwa zakat tidak sebatas mekanisme redistribusi kekayaan, melainkan juga instrumen penguatan ekonomi dan ketahanan nasional. Ia mencontohkan sejarah Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, ketika zakat dimasukkan ke dalam qonun (peraturan kerajaan) sebagai bagian dari perjuangan masyarakat. “Zakat saat itu digunakan untuk membangun logistik perang dan memperkuat pertahanan,” paparnya.
Direktur Akademizi Nana Sudiana menambahkan dimensi hukum dalam perjalanan zakat nasional. Ia menyoroti judicial review UU Zakat di Mahkamah Konstitusi (MK). “Proses panjang itu menjadi bagian perbaikan bangsa. UU Zakat lahir pada 1999, dan sesungguhnya Presiden BJ Habibie layak disebut bapak zakat Indonesia,” ungkap Nana.
Dosen Sejarah UI Agus Setiawan memaparkan perjalanan panjang praktik zakat di Indonesia, mulai dari masa awal kedatangan Islam hingga era modern. Menurutnya, zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat.
Agus menjelaskan, sejak awal kedatangan Islam, zakat telah menjadi rukun yang wajib ditunaikan setiap Muslim. “Amal perbuatan seperti salat, zakat, dan silaturahim menjadi jalan menuju surga. Namun kesadaran umat dalam berzakat tidak sekuat salat dan puasa,” ujarnya.
Pada masa kesultanan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sumber pendanaan pertahanan. “Zakat bahkan digunakan untuk membiayai perang. Kesultanan mengeluarkan perintah zakat,” kata Agus.
Di Kesultanan Aceh, misalnya, pengelolaan zakat dilakukan secara sederhana dan umumnya dihimpun pada bulan Ramadan. Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dibentuk untuk mengatur distribusi kepada masyarakat. Namun, banyak naskah sejarah Aceh tentang pengelolaan zakat kini dijual ke peneliti asing, membuat sebagian catatan sejarah sulit dilacak.
Memasuki abad ke-20, berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam mulai mengorganisir pengumpulan zakat. KH Ahmad Dahlan menjadi salah satu tokoh yang aktif menggerakkan pengumpulan zakat secara terstruktur.
Namun, pemerintah kolonial Belanda memandang pengelolaan zakat yang masif sebagai ancaman. “Telik sandi penjajah menilai zakat dapat digunakan untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah kolonial melarang pengumpulan zakat,” papar Agus.
Pada masa kolonial, kemiskinan merajalela dan jumlah mustahik (penerima zakat) meningkat, sementara ekonomi masyarakat menurun. Praktik pengelolaan zakat melalui baitul mal bahkan membuat penjajah Jepang khawatir akan potensi perlawanan.
Setelah kemerdekaan, mulai muncul gagasan pembentukan lembaga amil zakat, meski kondisi saat itu belum memungkinkan untuk mengelola secara nasional. Baru pada era Orde Baru, kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan zakat semakin kuat.
“Puncaknya adalah pada 1999, ketika lahir Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Ini menandai dimulainya era baru pengelolaan zakat secara resmi dan terstruktur oleh negara,” jelas Agus.
Agus menegaskan, perjalanan zakat di Indonesia merupakan bukti bahwa zakat bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan juga kekuatan sosial dan ekonomi yang mampu menggerakkan masyarakat dari masa kesultanan hingga era modern.
Ketua Dewan Pengurus Dompet Dhuafa, Ahmad Juwaini, menegaskan bahwa perjalanan panjang regulasi zakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran masyarakat sipil.
“UU Zakat pertama lahir setelah perjalanan panjang. Sebelum negara hadir, masyarakat sudah lebih dulu mengelola zakat, misalnya lewat BAMUIS BNI pada 1967, kemudian Dompet Dhuafa tahun 1993, dan Forum Zakat (FOZ) tahun 1997,” ujar Juwaini.
Ia menambahkan, FOZ pernah menggelar Munas pertama pada Januari 1999, hanya dua hari sebelum audiensi dengan Presiden BJ Habibie. “Sejak saat itu, empat kali Munas FOZ selalu dibuka oleh presiden, mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY,” jelasnya.
Akhirnya, pada 23 September 1999, DPR mengesahkan UU Zakat pertama. Juwaini mengingatkan, dalam pembahasan sempat muncul pertanyaan kritis di parlemen: “Kenapa harus ada UU Zakat, apakah nanti akan ada UU Salat?” Namun, tokoh zakat Didin Hafidhuddin menegaskan, zakat berbeda karena jika tidak ditunaikan, berarti merampas hak warga miskin.
Peneliti senior IDEAS, Yusuf Wibisono, menambahkan, praktik zakat di Indonesia sudah ada sejak awal masuknya Islam. Namun secara regulatif, upaya negara baru muncul di era Orde Baru.
“Pada Juli 1967, Departemen Agama pernah mengajukan RUU Zakat ke DPR Gotong Royong. Lalu, pada 1968 terbit PMA No. 4 dan 5 tentang pendirian BAZ dan Baitul Mal di seluruh daerah. Namun kebijakan ini tidak mendapat dukungan Presiden Soeharto dan akhirnya dianulir pada 1969,” ungkap Yusuf.
Menariknya, pada Oktober 1968 Soeharto bahkan sempat mendeklarasikan diri sebagai amil zakat nasional personal, sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 1970.
Meski demikian, pasca itu bermunculan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) bentukan pemerintah provinsi, mulai dari DKI Jakarta (1968), Kaltim (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), hingga berbagai provinsi lainnya. Gelombang pendirian BAZIS semakin kuat setelah terbit SKB Mendagri dan Menag No. 29/1991 dan No. 47/1991 yang memberi dasar legalitas.
Memasuki 1980-an, muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis korporasi, seperti BAMUIS BNI (1985), LAZ Yaumil PT Badak LNG (1986), dan Maal Pupuk Kujang (1994).
Dalam periode yang sama, lahir pula LAZ dari masyarakat sipil: Yayasan Dana Sosial Al Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1994), Rumah Zakat Indonesia (1998), Pos Keadilan Peduli Ummat (1999), dan DPU Daarut Tauhid (1999).
“Gelombang kemunculan organisasi pengelola zakat ini berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan naiknya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia,” jelas Yusuf.
Meski begitu, konsensus akhirnya lahir lewat UU Zakat 1999 yang mengakui peran negara sekaligus memberi ruang luas bagi masyarakat sipil untuk mengelola zakat.
“Sejarah zakat di Indonesia membuktikan, umat Islam tidak boleh dilarang menjalankan ibadahnya, sekaligus menegaskan zakat sebagai instrumen penting pengentasan kemiskinan,” pungkas Juwaini.