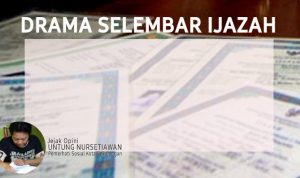Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat politik
Di negeri ini, janji sering kali lahir dengan wajah manis, namun kenyataan kerap berjalan dengan arah yang berbeda. Di tengah gegap gempita politik yang dipenuhi jargon pembangunan, rakyat justru menyaksikan kenyataan pahit: kabar pemutusan hubungan kerja massal di salah satu raksasa industri rokok, Gudang Garam. Sebuah kabar yang tidak sekadar menyinggung nasib ribuan buruh, melainkan juga mengguncang keyakinan terhadap janji-janji besar pemerintah baru yang menyebut akan menciptakan 19 juta lapangan kerja di bawah bendera Kabinet Merah Putih. Dua hal ini, di satu sisi adalah realitas, dan di sisi lain adalah mimpi yang masih melayang-layang di langit retorika.
PHK Gudang Garam bukanlah peristiwa yang sederhana. Ia bukan hanya soal perusahaan yang memangkas beban biaya operasional akibat menurunnya konsumsi rokok, atau desakan regulasi yang semakin menekan industri tembakau. Ia adalah potret getir dari rapuhnya lapangan pekerjaan di sektor formal, yang selama ini menjadi sandaran bagi jutaan keluarga. Para buruh yang telah bertahun-tahun bekerja dengan peluh dan tenaga, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa pengabdian mereka tidak lagi dibutuhkan. Bukan hanya mata pencaharian yang hilang, melainkan juga harga diri, rasa aman, dan masa depan anak-anak mereka.
Bagi Siti, seorang buruh linting rokok yang sudah dua puluh tahun mengabdikan diri, pabrik bukan sekadar tempat kerja, melainkan bagian dari hidupnya. Setiap pagi ia berangkat dengan seragam sederhana, membawa bekal nasi bungkus dari rumah, dan pulang menjelang senja dengan upah yang pas-pasan. Dari keringatnya, ia mampu menyekolahkan dua anaknya hingga bangku SMA. Namun, ketika kabar PHK diumumkan, dunia Siti runtuh seketika. Ia pulang dengan mata sembab, tak sanggup menjawab pertanyaan anaknya yang menunggu di rumah: “Bu, besok Ibu masih kerja?” Pertanyaan polos itu menyayat lebih tajam daripada keputusan manajemen yang dingin.
Kisah serupa juga dialami Budi, seorang buruh gudang yang setiap hari memanggul karton rokok. Tubuhnya yang kekar adalah bukti dari kerja keras bertahun-tahun. Namun, kini ia harus kembali ke kampung halaman dengan tangan kosong. Ia mencoba menghibur diri dengan berkata bahwa masih ada sawah milik orang tuanya yang bisa digarap. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa kembali ke desa bukanlah solusi. Di sana, lapangan pekerjaan justru semakin sempit, dan hasil sawah tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.
Cerita-cerita seperti Siti dan Budi adalah wajah nyata dari ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan. Mereka bukan angka dalam laporan ekonomi, mereka adalah manusia dengan keluarga, cita-cita, dan tanggung jawab. Mereka adalah rakyat yang setiap hari mendengarkan janji-janji besar dari para penguasa, tetapi justru harus menelan pil pahit kehilangan penghidupan.
Di sisi lain, janji 19 juta lapangan kerja yang didengungkan Kabinet Merah Putih seakan hadir sebagai obat penenang. Ia lahir dari mimbar kampanye, diteriakkan dengan penuh keyakinan, dan disambut dengan harapan rakyat kecil yang ingin keluar dari jerat kemiskinan. Janji itu seakan menjadi cahaya di tengah kegelapan. Namun, cahaya itu kini berhadapan dengan kenyataan pahit yang justru menunjukkan arah sebaliknya: lapangan kerja hilang, bukan bertambah. Bagaimana mungkin janji menciptakan 19 juta lapangan kerja diwujudkan, jika perusahaan-perusahaan besar saja tidak mampu menjaga stabilitas tenaga kerjanya?
Bila kita menoleh ke belakang, janji besar soal lapangan kerja bukan hal baru. Setiap presiden, setiap kabinet, selalu datang dengan komitmen serupa: membuka jutaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada masa pemerintahan sebelumnya, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia misalnya, pernah menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Pada periode berikutnya, jargon “revolusi mental” dan pembangunan infrastruktur juga digadang sebagai pintu pembuka lapangan kerja baru.
Nyatanya, angka pengangguran memang sempat menurun, tetapi tidak sedikit buruh yang justru terjebak dalam status kerja kontrak dan outsourcing yang jauh dari kata layak.
Kini janji itu kembali hadir dengan angka yang lebih fantastis: 19 juta lapangan kerja. Namun rakyat sudah belajar dari pengalaman, bahwa janji besar tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Ketika pabrik-pabrik besar justru merumahkan buruh, ketika startup digital melakukan efisiensi dengan gelombang PHK, ketika industri tekstil mengeluh karena kalah bersaing dengan produk impor murah, rakyat sulit percaya bahwa janji 19 juta lapangan kerja bisa tercapai tanpa perubahan yang radikal.
Rakyat kecil tentu tidak bisa hidup dari janji statistik. Mereka tidak bisa menunggu satu dekade hanya untuk melihat angka-angka pengangguran menurun di atas kertas. Mereka butuh pekerjaan hari ini, bukan esok. Mereka butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Setiap keluarga yang kehilangan penghasilan berarti ada anak-anak yang terancam putus sekolah, ada ibu-ibu yang menahan lapar, ada ayah-ayah yang kehilangan harga diri. Janji politik, tanpa realisasi nyata, hanya akan menambah luka sosial yang semakin dalam.
Indonesia sering kali membanggakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkisar di angka lima persen per tahun. Namun pertumbuhan itu tidak otomatis menciptakan lapangan kerja. Ada paradoks di sini: ekonomi tumbuh, tetapi kesempatan kerja justru stagnan atau bahkan berkurang. Kasus Gudang Garam membuktikan hal itu.
Perusahaan dengan sejarah panjang, dengan kontribusi besar pada penerimaan negara, justru tidak mampu mempertahankan buruhnya di tengah tekanan global dan regulasi domestik. Jika perusahaan sebesar itu saja limbung, bagaimana nasib industri kecil dan menengah? Bagaimana mungkin janji 19 juta lapangan kerja dapat diwujudkan tanpa perubahan struktural yang mendasar?
Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang benturan dua dunia: dunia janji dan dunia kenyataan. Dunia janji yang dipenuhi angka-angka besar, dan dunia kenyataan yang dipenuhi tangisan buruh yang kehilangan nafkah. Antara janji 19 juta lapangan kerja dan PHK massal Gudang Garam, rakyat berada di tengah, di persimpangan antara harapan dan kekecewaan.
Sejarah akan mencatat, apakah Kabinet Merah Putih benar-benar mampu menepati janji besarnya, ataukah ia hanya menambah daftar panjang pemerintahan yang menjanjikan bulan dan bintang, namun gagal memberikan sebutir beras di piring rakyat. Rakyat menunggu, bukan dengan sabar tanpa batas, tetapi dengan mata waspada dan hati yang terluka. Sebab janji yang tidak ditepati bukan hanya kebohongan, melainkan pengkhianatan terhadap harapan. Dan pengkhianatan itu, cepat atau lambat, akan berbalik menjadi luka kolektif bangsa.