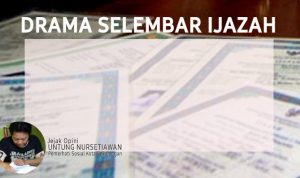Oleh: Ahmad Basri (Ketua Kajian Kritis Kebijakan Publik Pembangunan / K3PP – Alumni UMY 92)
Bicara fanatisme merupakan sejarah panjang tentang kehidupan manusia itu sendiri. Fanatisme seseorang dalam struktur sosial tradisional primitif maupun modern tetaplah sama. Semua Lahir dari rasa kecintaan terhadap obyek yang dilihatnya. Akan melahirkan persepsi dan keyakinan personal maupun kelompok. Dan persepsi sesungguhnya merupakan bentuk “bayangan” yang tidak mewakili obyek atas apa yang di lihat dan di rasakan. Bukan merupakan bentuk realitas yang sesungguhnya.
Fanatisme dapat di simbolkan dalam berbagai macam bentuk ideologi politik maupun keyakinan nilai – nilai keagamaan. Selama masih ada kata ” cinta ” dalam hati manusia. Fanatisme akan selalu mengikutinya secara alamiah. Sebab dalam fanatisme ada dogma – dogma “suci”, terkadang mengabaikan dan cenderung bermuara pada pemikiran irasional. Rasionalitas cenderung terabaikan dari apa yang di cintai dan kagumi. Dalam sejarah umat manusia fanatisme terbesar lahir dalam perspektif teologi keagamaan dan ideologi politik.
Masing – masing memberikan satu doktrin pemikiran monolitik keagamaan tentang satu kebenaran tunggal. Keduanya telah menyumbangkan sejarah peradaban manusia dalam berbagai macam pencapaian tujuan kehidupan. Dan kedua juga telah menyumbangkan persamaan yang hampir sama dalam sejarah konflik peradaban umat manusia. Jutaan manusia terbunuh saling membunuh tidak terhitung jumlahnya atas nama nilai keyakinan fanatisme. Tidak ada batasan rasional dalam mempertahakan sebuah keyakinan cenderung terabaikan. Karakter dan sifat irasional lebih mendominasi dalam diri personal maupun kelompok.
Itulah mengapa terkadang kesucian nilai – nilai agama cenderung “ternoda” menjadi bumerang ketika di dalamnya tumbuh semangat fanatisme yang berlebihan. Semua agama yang ada cenderung bergerak melahirkan semangat fanatisme. Dalam batasan rasional fanatisme itu juga diperlukan untuk menjaga “napas” keagamaan. Tanpa fanatisme apapun bentuknya akan menjadi benda purbakala. Oleh karna itu fanatisme dalam batasan rasional di perlukan agar tidak melahirkan sifat fanatik irasional.
Jika sampai pemikiran fanatik sebagai dogma tujuan, tentu akan melahirkan monopoli kebenaran, akan menampikan meniadakan yang lainnya. Itulah bahayanya sifat fanatisme obsolutisme. Menurut Robles bahwa, fanatisme digambarkan sebagai suatu kepatuhan penuh gairah tanpa syarat, antusiasme yang berlebihan terhadap suatu hal tertentu, keras kepala, tanpa pandang bulu atau menggunakan cara-cara dengan kekerasan. Sedangkan menurut Goddard fanatisme merupakan keyakinan yang membuat seseorang buta sehingga mau melakukan segala hal apapun demi mempertahankan keyakinan yang dianutnya.
Jika kita kaitkan dengan kontek politik pemilu tentang pilpres 2024, maka gejala fanatisme sudah mulai sedikit banyak menguat di tengah kehidupan masyarakat. Polarisasi sosial ideologi politik mulai terbuka secara lebar. Walaupun polarisasi fanatisme bukan sesuatu yang baru dalam dinamika politik di Indonesia. Setiap menjelang pemilu pilpres pasti akan muncul gejala sosial ideologi politik fanatisme. Tentunya dalam tingkat kadar yang berbeda. Namun mulai muncul menguat dan mengkristal sejak pemilu pilpres 2014 – 2019 antara Jokowi – Prabowo.
Pemilu pilpres sebelumnya tidak menguat, apalagi mengkristal di tengah masyarakat. Tidak melahirkan prilaku fanatisme yang ekstrem. Aroma wajah demokrasi berjalan dengan damai. Kemenangan SBY dua kali tidak menghasilkan polarisasi fanatisme apalagi euforia yang berlebih – lebihan. Tidak ada nama istilah politik apapun untuk menyebutkan satu kelompok dengan kelompok lain. Seperti kadrun – cebong. Ini lahir di era Jokowi – Prabowo termasuk istilah buzzerrp. Ironisnya, itu semua cenderung dibangun dan di pelihara agar tetap ekses demi kepentingan politik prakmatisme sesaat.
Oleh karna itu pemilu pilpres 2024 setidaknya harus melahirkan fanatisme rasional bukan irasional. Kita tinggalkan jejak “hitam” pemilu pilpres 2014 – 2019 yang telah melahirkan fanatisme irasional. Pelajaran berharga untuk tidak mengulang kembali budaya nama istilah “kadrun – cebong” dalam pemilu pilpres 2024. Sebuah keniscayaan sejarah dalam masyarakat hitrogenitas (pluralisme majemuk) dengan berbagai latar belakang unsur ( Agama, Etnis, Suku, Bahasa , Warna Kulit ) pasti akan selalu melahirkan budaya fanatisme. Berbeda dengan dengan masyarakat yang berkarakter homogenitas cultura, fanatisme tidak begitu kuat mencul kepermukaan karna diikat oleh satu kesamaan emosional identitas yang sama.
Dalam masyarakat homogenitas cultural, politik pembangunan demokrasi lebih mudah maju dan berkembang seperti di AS misalkan. Namun berbeda dengan masyarakat hitrogenitas cultural majemuk plural (Indonesia) pembangunan politik demokrasi seperti berjalan terseok – seok. Walaupun nampak ada pembangunan politik demokrasi, yang ditandai dengan ritual pemilu lima tahunan sekali, akan tetapi masih bersifat tahapan politik prosedural demokradi. Dimana esensial subtansial nilai – nilai demokrasi cenderung terabaikan. Pemilu dengan slogan azas luber cenderung sebatas teoritik tanpa realitas.
Adanya KPU – BAWASLU tidak memberikan satu jaminan bahwa azas luber dapat berjalan normal. Pola – pola keterlibatan aparat alat negara dan birokrasi negara masih bisa di rasakan dan cenderung menjadi tidak netral. Politik kekerasan intimidasi mudah terjadi. Inilah salah satu tantangan terbesar pembangunan demokrasi di Indonesia. Pandangan penulis sederhana, selama penyelangara pemilu dan aparat alat negara dan birokrasi negara tidak netral, maka fanatisme ( politik kebencian ) akan sulit di hilangkan dan akan selalu hadir. Polarisasi sosial atas nama fanatisme akan terus terjadi. Konflik – konflik akan terus mewarnai ditengah masyarakat sebagai warisan dendam politik.
Munculnya berbagai banyak nama capres pemilu 2024, setidaknya harus dimaknai secara positif bahwa, itu semua memberikan satu tanda pembangunan demokrasi telah berjalan dan hidup di tengah hitrogenitas cultural (pluralisme majemuk) kehidupan masyarakat. Bahwa masing – masing capres akan melahirkan berbagai macam fenomena fanatisme dan merupakan keniscayaan yang harus di kelolah secara positif bukan negatif. Fanatisme harus di tempatkan dalam keridor berpikir rasional bukan irasional terhadap para capres. Menolak kehadiran capres / menolak seseorang menjadi capres merupakan sebuah bentuk kemuduran dalam berdemokrasi. Fanatisme terhadap capres tertentu tidak harus melahirkan politik kebencian pada capres lainnya. Hari ini kita masih di pertontonkan fanatisme capres melahirkan politik kebencian. Dan itu tidak boleh terjadi…