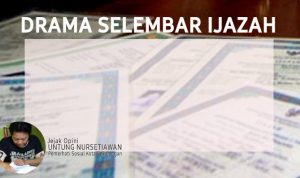Oleh: Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan
Kasus kepala SMAN 1 Cimarga Banten yang menampar siswa karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah, lalu dituntut oleh orang tua siswa hingga terancam dipecat oleh gubernur, benar-benar menyentak nurani publik. Teman-teman siswa tersebut juga ikut-ikutan mogok belajar sebagai bentuk solidaritas katanya. Sebuah ironi yang menunjukkan bahwa sejatinya mereka pun sebenarnya tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi sistem, hukum, dan cara berpikir masyarakat kini seolah membalik nilai-nilai itu: guru yang menegakkan disiplin dituding melakukan kekerasan, sementara siswa yang melanggar aturan justru “dibelai” atas nama hak asasi.
Fenomena ini bukan sekadar soal satu tamparan. Ia adalah cermin rusaknya tatanan pendidikan kita hari ini—ketika batas antara kebebasan dan kebiadaban menjadi kabur. Dalam semangat “Kurikulum Merdeka”, kata “merdeka” sering disalahartikan sebagai bebas tanpa batas, tanpa adab, dan tanpa hierarki. Padahal, “merdeka belajar” bukan berarti bebas melakukan apa saja, melainkan bebas mengembangkan potensi di bawah bimbingan nilai, tanggung jawab, dan moralitas.
Pertanyaan yang menggelitik: jika merokok saja dibiarkan, bagaimana nanti jika siswa kedapatan mengonsumsi narkoba? Apakah guru akan kembali disalahkan jika mencoba menegur dengan keras? Apakah semua bentuk disiplin harus dibungkus lembut, tanpa boleh menyentuh ego anak, sementara perilaku buruknya dibiarkan tumbuh liar atas nama “hak asasi”?
Kita sedang menyaksikan fenomena terbalik: guru kehilangan wibawa, sekolah kehilangan kendali, dan siswa kehilangan rasa hormat. Guru yang dulu disebut “pahlawan tanpa tanda jasa” kini lebih mirip “tersangka tanpa pembelaan”. Satu tindakan spontan karena panggilan tanggung jawab bisa berujung sanksi administratif, laporan polisi, atau bahkan pemecatan. Masyarakat kita makin sensitif terhadap “tamparan”, tapi makin kebal terhadap degradasi moral.
Di masa lalu, guru boleh marah, boleh menegur keras, bahkan kadang menampar jika murid benar-benar melanggar batas. Itu bukan karena guru benci, tetapi karena cinta—karena ingin mendidik. Tamparan guru dulu menyadarkan, bukan menyakiti. Namun kini, sistem hukum dan persepsi sosial memaknai disiplin sebagai kekerasan, dan kasih sayang dalam bentuk ketegasan sebagai pelanggaran hak anak.
Padahal, hak anak tidak bisa dilepaskan dari kewajiban anak. Hak untuk dihormati datang setelah kewajiban untuk menghormati. Hak untuk dididik datang bersama tanggung jawab untuk belajar. Jika anak merasa bebas melakukan apa pun tanpa konsekuensi, maka pendidikan kehilangan maknanya. Tidak ada lagi ruang bagi pembentukan karakter, hanya ada tuntutan atas kenyamanan pribadi.
Kurikulum Merdeka sejatinya dimaksudkan untuk membebaskan kreativitas guru dan siswa dari belenggu birokrasi, bukan untuk meniadakan norma dan adab. Tetapi ketika “kemerdekaan” ditafsir secara ekstrem, ketika setiap teguran dianggap kekerasan, dan setiap hukuman dianggap pelanggaran HAM, maka pendidikan berubah menjadi arena kebingungan moral.
Kini kita harus jujur bertanya: masihkah ada tempat bagi guru untuk mendidik dengan hati sekaligus ketegasan? Atau dunia pendidikan kita akan terus terperosok menjadi ruang di mana guru hanya berani memberi nilai, tapi takut memberi teladan disiplin?
Kasus ini bukan sekadar soal tamparan di pipi seorang siswa. Ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan kita. Tamparan terhadap sistem yang kehilangan arah, terhadap masyarakat yang terlalu cepat menghakimi, terhadap kebijakan yang terlalu lemah melindungi pendidik.
Jika negara dan masyarakat terus membiarkan guru kehilangan wibawanya, maka jangan heran bila anak-anak kita tumbuh tanpa rasa hormat, tanpa batas, dan tanpa jiwa belajar yang sejati. Dunia pendidikan yang ideal tidak lahir dari ruang bebas tanpa aturan, melainkan dari keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kasih sayang dan ketegasan.
Mungkin inilah saatnya kita semua berhenti menuding guru, dan mulai bertanya: apakah kita masih menghormati mereka sebagaimana seharusnya?