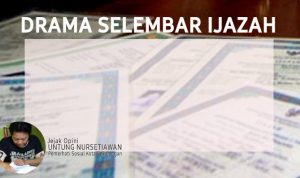Oleh: Firman Tendry Masengi
Indonesia hari ini bukan lagi republik yang hidup dari cita-cita, melainkan pasar besar tempat demokrasi dijual secara eceran dan hukum dilelang kepada penawar tertinggi. Kita menyebut diri sebagai negara hukum (rechsstaat), tetapi hukum telah kehilangan watak normatifnya. Ia tidak lagi menjadi “roh yang menuntun keadilan,” melainkan menjadi instrumen kuasa yang tunduk pada kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Inilah masa ketika republik menjelma menjadi oligarkokrasi — sistem yang mengawinkan kerakusan oligarki dengan proseduralisme demokrasi.
Oligarki Bertopeng Demokrasi
Dalam teori politik klasik, Aristoteles menulis bahwa oligarki adalah bentuk penyimpangan dari aristokrasi: kekuasaan yang seharusnya dijalankan oleh orang-orang terbaik, tetapi justru dikuasai oleh orang-orang kaya bajingan_ Demokrasi Indonesia hari ini tidak sekadar menyimpang — ia bertransformasi menjadi teater elektoral, tempat rakyat hanya menjadi figuran di panggung pesta politik yang dikoreografikan oleh pemilik modal.
Partai politik bukan lagi kanal ideologi, melainkan korporasi kekuasaan. Ia beroperasi seperti perusahaan: membutuhkan investasi besar, melahirkan loyalitas berbasis uang, dan menjual kebijakan kepada sponsor. Dari situ lahir hukum-hukum yang memihak, regulasi yang dipelintir, dan kebijakan publik yang didekte oleh kepentingan ekonomi segelintir elite.
Dalam ruang itu, demokrasi kehilangan “rasa malu” — ia tidak lagi berbicara tentang rakyat, tetapi tentang kontrak dagang antara kekuasaan dan modal.
Hukum Hamba Kekuasaan
Dalam sistem oligarkokrasi, hukum bukan lagi salus populi suprema kex esto (hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat), melainkan lex mercatoria potentiae — hukum yang melayani pasar kekuasaan. Proses penegakan hukum tidak lagi bergerak atas dasar keadilan substantif, tetapi atas dasar siapa yang membayar lebih atau siapa yang berkuasa lebih.
Keadaan ini menjadikan lembaga hukum tidak ubahnya “kuli politik”: bekerja bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi untuk memperhalus kebohongan yang sudah dilembagakan.
Dari kasus korupsi yang berlarut, skandal kekuasaan yang tertutup, hingga manipulasi hukum yang terang-terangan, rakyat menyaksikan bagaimana supremasi hukum berubah menjadi supremasi kehendak elite. Inilah yang disebut oleh Achille Mbembe sebagai necropolitics: kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak hidup dalam hukum dan siapa yang boleh mati di luar hukum.
Politik yang Menjadi Industri
Politik dalam oligarkokrasi tidak lagi menjadi jalan pengabdian, melainkan industri dengan rantai pasok yang kompleks. Dari pembiayaan partai, belanja elektoral, hingga lobi hukum dan proyek negara — semuanya beroperasi dengan logika pasar.
Dalam situasi seperti ini, politik kehilangan imajinasinya sebagai arena perjuangan ideologis. Ia tidak lagi membicarakan keadilan sosial atau kedaulatan rakyat, tetapi dividen kekuasaan, portofolio politik, dan return of investment.
Maka benarlah ungkapan Hannah Arendt: “The most radical revolutionary becomes a conservative the day after the revolution.” Para reformis berubah menjadi oligark baru, dan cita-cita reformasi berubah menjadi komoditas nostalgia.
Republik yang Kehilangan Arah
Ketika oligarki bersemayam di dalam demokrasi, republik kehilangan arah moralnya. Institusi publik lumpuh karena dipaksa melayani kepentingan privat. Media tersandera oleh iklan dan kepemilikan. Akademisi banyak yang kehilangan kebebasan berpikir karena tekanan dana riset atau jabatan struktural. Hukum menjadi alat legitimasi, bukan alat koreksi.
Masyarakat sipil pun terseret dalam apatisme yang berbahaya — menyerah pada keyakinan bahwa “semua sama saja,” padahal tidak semua demikian.
Dalam pandangan filsafat hukum progresif, seperti yang dikatakan oleh *Satjipto Rahardjo*, hukum seharusnya menjadi alat emansipasi sosial, bukan alat represi politik. Namun, dalam sistem oligarkokrasi, hukum justru menjadi benteng eksklusif bagi kepentingan elite untuk mempertahankan privilese mereka. Itulah mengapa rule of law bergeser menjadi rule by law — hukum tidak menundukkan kekuasaan, tetapi digunakan oleh kekuasaan untuk menundukkan rakyat.
Masa Depan yang Terancam:
Jika kondisi ini dibiarkan, maka masa depan Indonesia akan mengarah pada paradoks tragis: republik tanpa rakyat. Demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan yang penuh sorak tetapi tanpa makna.
Hukum hanya akan menjadi katalog sanksi yang tak berdaya di hadapan privilese. Dan bangsa ini akan hidup dalam keadaan darurat moral permanen, di mana korupsi dianggap kebiasaan, ketidakadilan dianggap nasib, dan kebohongan dianggap strategi.
Indonesia akan menjadi “post-democracy”, istilah yang digunakan *Colin Crouch* untuk menggambarkan negara yang secara formal demokratis tetapi secara substantif dikuasai oleh korporasi dan elite ekonomi-politik. Dalam skenario ini, rakyat hanya akan menjadi penonton dalam film panjang yang disutradarai oleh para pemodal dan aktor politik yang berpura-pura menjadi pahlawan.
Rekonstruksi Harapan
Namun sejarah belum berakhir. Selama masih ada kesadaran moral dan nalar publik yang kritis, republik ini belum sepenuhnya jatuh. Kita membutuhkan _renaissance_ politik: kebangkitan kembali etika, logika, dan keberanian sipil untuk menuntut pertanggungjawaban.
Kita harus mengembalikan politik pada cita-cita aslinya — bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang untuk siapa kekuasaan itu digunakan.
Hukum harus dikembalikan ke tempatnya sebagai ratio legis, bukan ratio bisnis. Rakyat harus berani menuntut keadilan bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai hak konstitusional. Dan negara harus berhenti menjadi pabrik kompromi; ia harus kembali menjadi pelindung keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.
Negara Harus Kembali Beradab
Jika oligarkokrasi adalah penyakit, maka kesadaran rakyat adalah obatnya. Demokrasi tidak akan pulih dari atas, melainkan dari bawah — dari keberanian rakyat menolak tunduk pada ketidakadilan yang dilembagakan.
Negara ini harus kembali beradab; karena tanpa keadaban hukum dan moral, kita bukan lagi bangsa merdeka, melainkan sekadar koloni yang dikuasai oleh pemilik modal dengan bendera merah-putih sebagai hiasan.